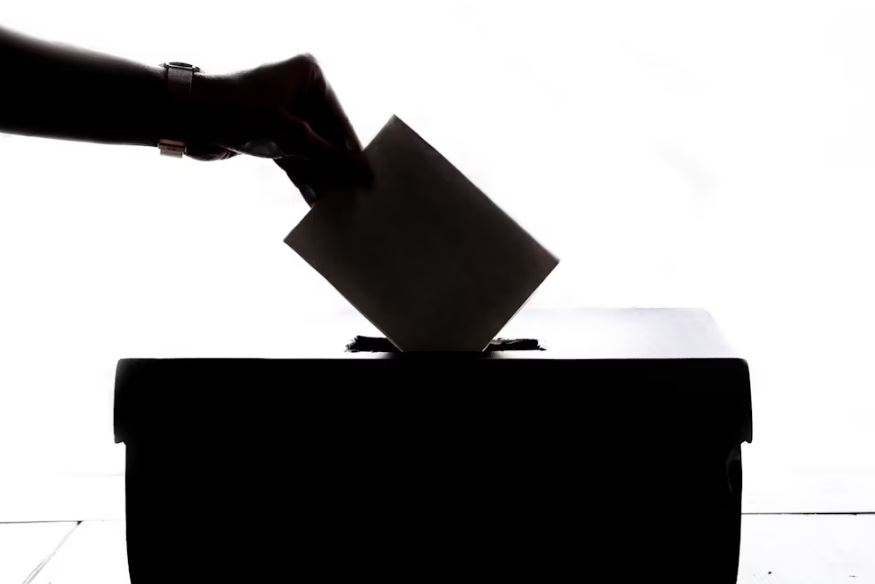Musim Pilkada, Musim Menabur Uang?
Oleh: Immawan Wahyudi, Immawan Wahyudi Dosen Fakultas Hukum (S1 dan S2) UAD
Ada tiga catatan utama dalam tradisi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang secara serentak akan diselenggarakan pada bulan November. Pertama, koalisi Pemilihan Presiden (Pilpres) masih menjadi hantu politik yang real. Dampak politiknya adalah ada kandidat yang diharapkan oleh warga masyarakat, tetapi oleh koalisi tanpa hati (karena semua partai berkoalisi) menghapus harapan warga masyarakat secara sistematis. Sisanya adalah sikap kontroversial antara lain: datanglah ke TPS tapi pilih semua kandidat atau tidak usah datang ke TPS. Kedua, sistem rekrutmen oleh Partai Politik (Parpol) tidak lagi mempertimbangkan verifikasi kandidat, apakah memiliki gagasan pemerintahan dan bersih dari KKN.
Kandidat dari alumni Lembaga Pemasyarakatan (LP) seolah digelarkan “karpet merah” untuk melanjutkan petualangan politiknya –termasuk mengulang tindak pidana yang telah menjebloskannya ke dalam LP. Ketiga, Money Politics (politik uang alias suap) masih –dan akan semakin-- dominan. Secara kasat mata realita sosial ini sesungguhnya telah memberikan peringatan dini bahwa kemungkinan (besar) para kandidat yang terpilih akan terjebak dalam lubang tindak pidana korupsi. Tetapi tidak akan ada lagi pihak yang peduli secara penuh terhadap kenyataan ini. Namun kita harus terus punya cita-cita menghidupkan semangat reformasi.
Kecelakaan Politik yang Tragis
Awal perhelatan politik demokrasi Pilkada tahun 2024 ini dimulai dengan dibukanya lembaran hitam: pembunuhan hak konstitusional warga yang sesungguhnya memiliki peluang untuk terpilih sebagai kepala daerah. Namun Pilkada kali ini ibarat dalam dunia bisnis yakni ada penawaran dan permintaan (supply and demand). Dalam konteks Pilkada ada yang dibutuhkan untuk berkuasa –tetapi tidak punya partai dan kurang dana. Ada juga tokoh yang butuh kekuasaan dan berlimpah dana tetapi kurang diminati oleh warga. Dalam alam dan etika sosial yang kian apatis terhadap persoalan etika kekuasaan maka person yang punya kedekatan politik dengan partai politik dan kelebihan dana lah yang akan digadang-gadang menjadi kandidat.
Urusan akan berbenturan dengan animo dan minat masyarakat untuk memilihnya bisa diatur dengan segala cara. Maka terbentuklah “legitimasi politik” berbasis transaksional. Transaksi pertama sudah terjadi transaksi antara kandidat dengan penguasa partai. Barulah yang kedua transaksi antara kandidat dengan pemilih dengan berbagai variasi, tetapi umumnya berbasis pada pemberian uang sesuai dengan “kelayakan” di lingkungan setempat.
Sebagaimana dinyatakan oleh Bambang Soesatyo –dalam video yang sudah beredar lama di media sosial—seorang Calon Anggota DPR bisa menghabiskan dana antara 6 miliar rupiah hingga 30 miliar rupiah. Jujurnya, Mantan Ketua MPR itu juga mengatakan, untuk itu diperlukan pemodal besar guna menyukseskan Caleg tersebut. Pada point inilah kita dengan gamblang dapat menelusuri bahwa proses politik demokrasi sudah sepenuhnya masuk dalam proses bisnis dalam komoditas perdagangan. Maksudnya, para kandidat terpilih pada saatnya harus membayar kembali dana dukungan dari pemodal berupa kebijakan-kebijakan yang pro pengusaha. Sesungguhnya warga masyarakat sudah mengetahui hal ini. Namun, diam saja, seolah-olah sudah menyetujui tradisi politik demokrasi menjadi politik bisnis ini.
Pada abad ke 3 SM, Aristoteles mengemukakan teori tentang oligarki yang dibaginya menjadi 4 (empat) varietas oligarki. Hal yang dikatakan Aritoteles dalam Politic itu, antara lain adalah “Di antara varietas oligarki ialah praktik pemerintahan yang didalamnya pemangkuan jabatan tergantung pada persyaratan harta benda cukup tinggi, sehingga menyisihkan kaum miskin untuk menduduki jabatan. Meskipun mereka membentuk mayoritas, tetapi disana dimungkinkan bagi siapapun yang mampu memenuhi jumlah harta benda yang ditetapkan untuk mempunyai bagian di dalam konstitusi.”
Apa yang dikatakan Aristoteles tidak berhenti pada kemungkinan tiap-tiap warga negeri dapat menjadi kandidat kepala daerah, karena cara yang paling kejam adalah dengan “membeli” semua partai untuk tidak mencalonkan seseorang. Dalam pengertian membeli ini bisa berupa uang tunai, bia jabatan dan bisa juga ancaman yang akhir-akhir disebut sebagai “politik penyanderaan/politik sandra.” Komentar yang tepat dan simpel adalah”tragis dan sadis.”
Kebiasaan Kecil yang Menyimpang
Seorang teman dari Kauman Jogja mengirim pesan: “Mas, sewaktu muktamar Muhammadiyah warga kita juga pada berebut (kaos). (Begitu juga) ketika di salah satu kampus kita, warga pada berebut kaos. Waktu itu sempat saya sampaikan agar jangan ada yang berebut, eee ternyata gagal juga. Ini sangat memprihatinkan.” Pesan wa itu disampaikan karena ada komentar saya terhadap aktivitas Presiden di Godean yang mengesankan semangat berebut memperoleh bagian dari lontaran hadiah yang biasanya dilakukan oleh Pak Presiden. Saya balas pesan wa tadi; “Nggih mas. Ini perubahan perilaku yang dipaksakan melalui cara pengkondisian seperti ini akan meninggalkan problem psiko-sosial yang menyisakan kondisi degeneratif –yang panjang. Perlu kiranya para kyai kita dalam memberikan tausiyah lebih konkret pada perilaku sosial menyimpang seperti ini.
Pada sisi lain pembiasaan melemparkan hadiah itu akan menjadi legitimasi etika sosial yang kemudian diberi nama "kedermawanan." Belum lama ini ada contoh konkret yang dilakukan oleh seorang calon kepala daerah yang lebih ngeri karena dengan menyebar uang sambal berdiri diatas mobil pick-up. Dampak dari cara-cara semacam ini akan menjadikan “money politics” masuk dalam kategori “abu-abu.” Misalnya ada pernyataan; “Lho wong diberi masak mau menolak.” Nah perilkau itu lama-lama menjadi “klangenan.” Menurut hemat penulis inilah sumber asli dari money politics, yang akhirnya akan terus berjalan menyatu dengan sikap pragmatis dan sangat mustahil untuk dikurangi apalagi dihapuskan.
Kita Harus Terus Berikhtiar
Sedemikian rupa bahaya money politics, maka tidak layak kita melepaskan diri dari tanggung jawab untuk merancang pemerintahan yang baik. Bagaimanapun kita harus terus mengawal pembentukan perundang-undangan yang layak untuk diimplementasikan dalam pemerintahan yang baik. Integritas moral elite pembentuk undang-undang sangat menghajatkan dukungan politik dari sikap kritis dan kesadaran hukum masyarakat.
Penanganan terhadap persoalan money politics dan korupsi yang terjadi tidak akan berjalan dengan baik manakala tidak ada pengawasan dan pressure dari masyarakat. Namun masyarakat tidak akan peduli tanpa ada kepentingan yang mereka harapkan tertunaikan. Lingkaran setan ini kemudian membentuk kebiasaan politik. Kebiasaan politik semacam ini memerlukan kepedulian dan sikap jihad kita melawan politik yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.
Rancangan sederhana dapat kita gagas, antara lain mengaktualisasikan program penolakan anti politik uang dalam aksi-aksi unjuk rasa, memperkuat jaringan masyarakat peduli politik bermartabat, terus memperbesar kesadaran hukum dan politik masyarakat, memperkuat politisi berintegritas moral tinggi, dan merancang norma-norma berbasis politik hukum anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pulis menyadari bahwa tetap ada kandidat kepala daerah yang bersih, berintegritas moral tinggi dan memiliki kapasitas yang cukup. Kepada kandidat semacam inilah yang seharusnya kita dukung dan kita pilih, untuk memelihara demokrasi yang bermakna bagi rakyat Republik Indonesia.*