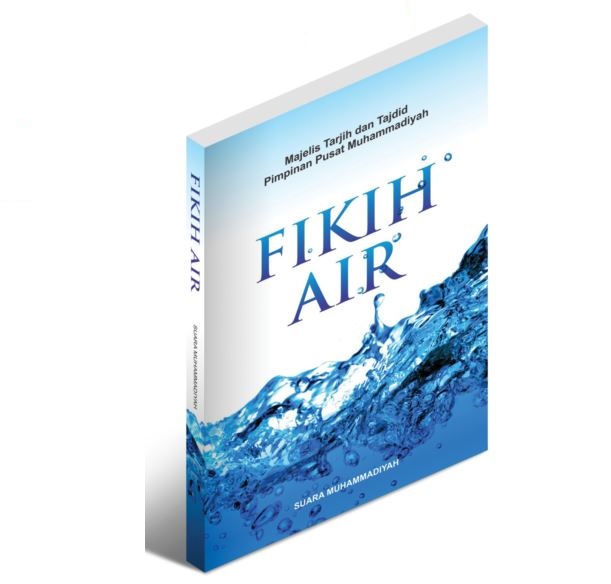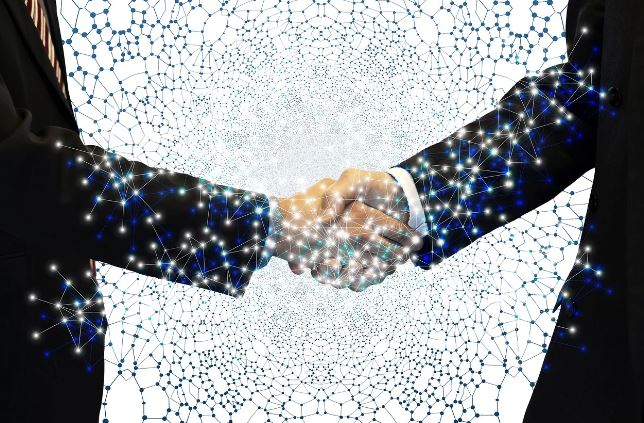Tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang Syarat Usia Capres-Cawapres
Oleh: Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA
Hari Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, bahwa syarat pendaftaran Capres-Cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau berpangalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saya menyampaikan sejumlah tanggapan untuk putusan MK tersebut. Tanggapan ini bersifat pribadi dan tidak mewakili institusi manapun.
Keputusan MK melampaui kewenangannya yang seharusnya hanya menjadi penjaga gawang konstitusi dan tidak menambah norma baru berupa syarat Capres-Cawapres adalah pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah. Norma baru ini seharunya menjadi wewenang pembentuk Undang-Undang (lembaga legislatif dan eksekutif). Saldi Isra (wakil ketua MK) dan tiga hakim lainnya berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan keputusan MK. Saldi mengaku bingung karena sejak 2017 dirinya menjadi hakim MK, baru kali ini mengalami peristiwa “aneh” dan “luar biasa”. MK disebut Zainal Arifin Mochtar sebagai perusak open legal policy secara serampangan.
Sebenarnya tidak ada masalah menurunkan batas usia Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau bahkan hingga ke 21 tahun. Capres-cawapres usia muda juga terjadi di sejumlah negara demokrasi lain. Persoalannya, proses perubahan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa menjelang pendaftaran Capres-Cawapres sebagai kado dari paman buat ponakan. Seharusnya perubahan itu lebih etis dilakukan melalui jalur konstitusional, yaitu pembahasan di DPR RI berupa revisi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dan itu bisa dilakukan setelah 2024 agar tidak terjadi kegaduhan yang berakibat pada buruknya kualitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Putusan MK tersebut terbaca secara jelas merupakan hadiah untuk putra mahkota Gibran (walikota Solo), bukan untuk AHY, bukan untuk Erick, bukan untuk Muhadjir apalagi Ridho Al-Hamdi. Merespon keputusan MK tersebut, Jokowi yang sedang berada di Tiongkok menyampaikan bahwa itu adalah wewenang MK dan partai politik pengusung capres-cawapres. Ini pernyataan normatif. Wajar jika publik berpendapat, Jokowi merestui keputusan MK. Untuk menepis tuduhan “politik dinasti”, Jokowi sebaiknya mengatakan “Gibran tidak akan maju sebagai cawapres”. Tapi apa berani?
Gibran jadi cawapres adalah skenario yang sudah didesain secara jelas. Ketua MK (Anwar Usman) adalah adik ipar Jokowi. Kaesang (putra bungsu Jokowi) dipasang sebagai ketum PSI yang mendukung pencapresan Prabowo, padahal sebelumnya PSI dukung Ganjar sebagai capres. Partai politik koalisi Jokowi juga direstui mendukung Prabowo sebagai capres. Projo dimana Jokowi sebagai Pembina juga merapat ke Prabowo. Ini semua tentu sudah by designed. Tidak ada yang kebetulan dalam politik.
Jokowi sedang membangun “dinasti politik”? Pengagum Jokowi tentu menolak pernyataan ini karena semua proses dilalui secara demokratis. Gibran dan Bobby Nasution dipilih melalui Pilkada. Kaesang pun ditetapkan melalui mekanisme internal PSI. Betul, semua dilalui secara demokratis tetapi prosesnya dibajak seolah-olah dikesankan demokratis padahal tidak. Semua jalur sudah diatur agar mengarah pada satu putusan.
Pihak yang terdampak (kebakaran jenggot) atas putusan MK ini adalah PDIP dan Ganjar. Soliditas PDIP diuji, apakah basis suara di Jawa Tengah tetap untuk Ganjar atau malah membelot ke Prabowo (jika berpasangan dengan Gibran). Pesan Goenawan Mohamad dan Butet Kartaredjasa sebagai pendukung setia Jokowi pun tak digubris sama sekali. Puzzle ini menjadi tanda bahwa Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang Megawati dan PDIP.
Sekarang, putusan MK sudah diketok: final and binding (final dan mengingat). Tidak bisa dirubah lagi. Gibran punya peluang. Namun, Jokowi masih bisa melarang sang putra sulung untuk maju sebagai cawapres agar mewariskan citra baik keluarga dan bukan bagian dari pengamal “dinasti politik”. Ini juga dilakukan untuk memulihkan nama baik MK agar tidak diberi stempel sebagai “Mahkamah Keluarga” yang kini tengah menjadi buah bibir di masyarakat.
Apakah lantas jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, pertandingan akan dimenangkan Prabowo-Gibran? Kekuatan Anis-Muhaimin (AMIN) tidak bisa diremehkan karena ini adalah gabungan kekuatan santri yang menjadi simbol persatuan kaum Muslim di mana Muslim masih menjadi mayoritas di republik ini. Begitu juga PDIP tidak akan tinggal diam sebagai partai pemenang pemilu dua kali tentu akan bertarung habis-habisan dengan kekuatan para bantengers di akar rumput. Menarik disimak wawancara Rosi dengan dengan Made Supriatma di Kompas TV dengan tema “Antara Jokowi, Gibran, dan Ketua Mahkamah Konstitusi”.
Putusan MK ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya bagian babak yang berserak dari episode drama politik (drapol) dengan banyak sutradara dan penulis skenario yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, setidaknya kita bisa mengucap “innalillahi wa inna ilaihi rojiun” atas wafatnya penjaga gawang konstitusi bernama “Mahkamah Konstitusi”. Mari kita takziyah untuk MK. Alfatihah.
Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Wakil Dekan Bidang Akademik FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta