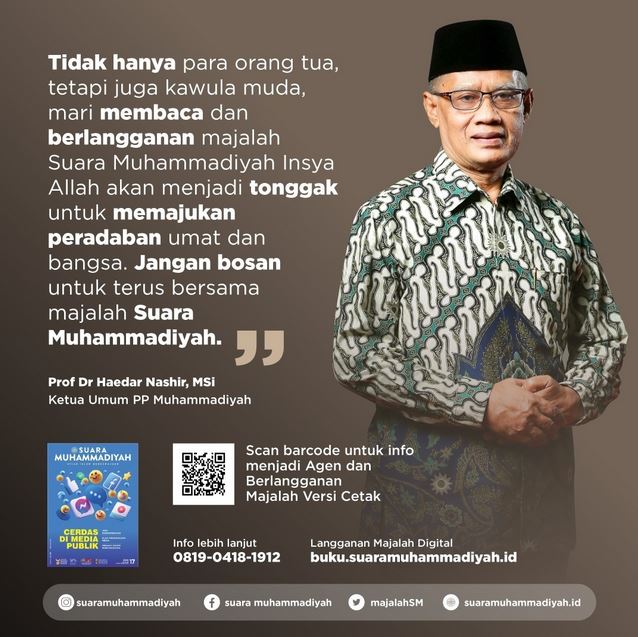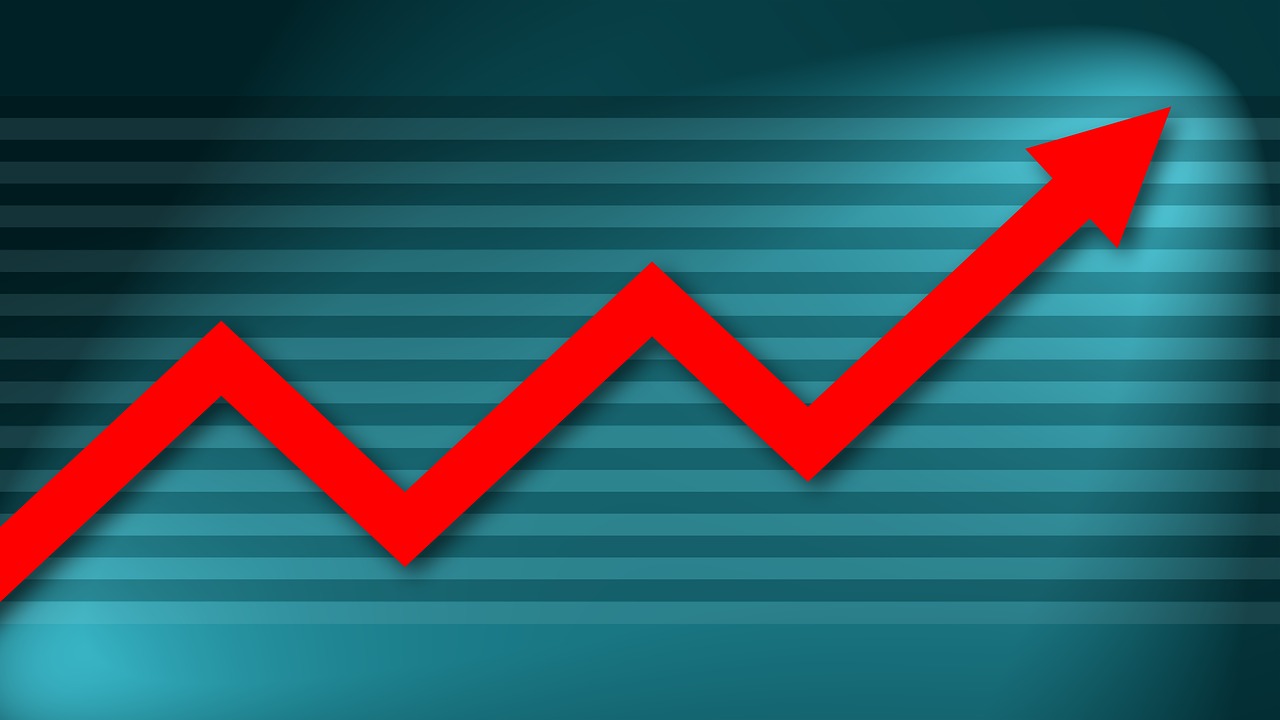Muhammadiyah Minangkabau: Satu Abad Refleksi dan Arah Masa Depan
Oleh: Riki Saputra, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Memasuki satu abad kehadiran Muhammadiyah di Minangkabau merupakan momen reflektif yang bukan sekadar perayaan sejarah, tetapi juga momentum filosofis untuk membaca bagaimana sebuah gerakan modernis Islam bertransformasi di tanah yang kaya tradisi, adat, dan dinamika intelektual. Di Minangkabau dengan semboyannya “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Muhammadiyah hadir bukan sebagai kekuatan asing, melainkan sebagai katalis yang menafsir ulang relasi adat dan syarak dalam horizon kemajuan. Karena itu, 1 abad perjalanan ini menyimpan kisah yang tidak hanya informatif, tetapi sarat makna filosofis tentang perubahan, dialog, dan kedewasaan intelektual.
Rasionalitas dan Etos Pembaruan dalam Lintasan Sejarah
Sejak awal berdirinya pada 1912, Muhammadiyah berangkat dari semangat tajdid, yakni kembali kepada kemurnian Islam dan rasionalitas. Ketika Muhammadiyah masuk ke Minangkabau pada 1925, ia menemukan tanah yang subur, kultur debat keagamaan, tradisi keilmuan surau, serta dinamika pembaruan yang telah dirintis ulama Minang seperti Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan murid-muridnya, termasuk Haji Rasul (Syekh Abdul Karim Amrullah).
Salah satu kisah menarik yang dituturkan Hamka memperlihatkan bagaimana dinamika rasionalitas Muhammadiyah bekerja bahkan di ranah personal. Hamka menceritakan bahwa ayahnya, Haji Rasul, awalnya sangat menolak gagasan bahwa perempuan boleh berbicara di depan laki-laki dalam forum resmi. Dalam perspektif budaya masa itu, keberatan tersebut dapat dipahami. Namun perdebatan yang hangat antara Haji Rasul dan Ki Haji Mas Mansur sebagai Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang menjadi titik balik yang menunjukkan elastisitas intelektual seorang ulama besar. Haji Rasul yang keras akhirnya luluh, menerima argumentasi Mas Mansur, dan mengakui kekeliruannya. Ini bukan sekadar anekdot sejarah tetapi ia mencerminkan kalau dalam istilah Kanti sapere aude, yakni keberanian untuk merevisi pandangan lama ketika berjumpa dengan argumentasi yang lebih benar.
Peristiwa ini bukan hanya tentang perdebatan dua ulama, tetapi tentang bagaimana tradisi keilmuan Minangkabau bersifat dialogis dan terbuka terhadap koreksi, yakni virtue penting dalam modernitas Islam.
Perempuan dalam Arena Publik Reinterpretasi Tradisi
Dalam konteks kongres Muhammadiyah pada masa itu, terdapat pula temuan menarik tentang tampilnya seorang tokoh perempuan muda, yakni istri Buya Hamka yang dikenal dengan panggilan “Umi”. Meskipun tidak pernah disebut tampil di ruang publik sebelumnya, dokumen kongres menunjukkan bahwa ia menjadi pembicara termuda pada saat itu. Ini menandai salah satu langkah penting dalam sejarah partisipasi perempuan di ruang publik keagamaan di Minangkabau.
Dari perspektif hermeneutika Gadamer, peristiwa ini adalah contoh fusion of horizons, yakni tradisi adat yang cenderung membatasi peran perempuan bertemu dengan horizon baru pemikiran Muhammadiyah yang lebih progresif. Dialog dua horizon tersebut melahirkan bentuk partisipasi baru tanpa menghapus identitas kultural Minangkabau. Begitu juga tentang Fort de Kock ke Nusantara Kongres yang Mengukuhkan Soliditas, sejarah mencatat bahwa hanya lima tahun setelah cabang pertama berdiri, Sumatera Barat menjadi tuan rumah Kongres Muhammadiyah ke-19 pada 1930. Kongres ini yang dikaji secara mendalam oleh sejarawan Fikrul Hanif Sofyan dalam bukunya Fort Dekok dan Depresi Ekonomi (2025) yang menjadi salah satu kongres terbesar yang pernah diselenggarakan Muhammadiyah di luar Jawa.
Ribuan orang dari berbagai penjuru Nusantara memadati Fort de Kock (Bukittinggi). Ini terjadi pada masa depresi ekonomi global, ketika banyak kegiatan besar justru gagal karena keterbatasan dana. Suksesnya kongres tersebut bukan sekadar prestasi organisatoris, tetapi bukti bahwa Muhammadiyah di Minangkabau telah memiliki basis sosial, jaringan saudagar, dan simpul-simpul pergerakan yang solid sejak awal. Dari perspektif teori sosial Habermas, kongres ini dapat dibaca sebagai public sphere Islam modern, yakni sebagai ruang di mana gagasan rasional, aspirasi sosial, dan visi keumatan dipertemukan secara terbuka untuk membentuk agenda kolektif.
Jejak Para Tokoh Dari Haji Rasul hingga AR Sutan Mansur
Awal mula keberadaan Muhammadiyah di Sumatera Barat tidak lepas dari perjalanan Haji Rasul ke Jawa untuk menjenguk putrinya, Fatimah Karim Amrullah, istri AR Sutan Mansur. Di sana ia menyaksikan langsung aktivitas sosial Muhammadiyah yang dianggap lebih maju dibandingkan gerakan serupa di Minangkabau. Pertemuannya dengan Kiai Ahmad Dahlan menjadi momen penting yang menguatkan ketertarikannya. Sebelum bergabung dengan Muhammadiyah, Haji Rasul telah memiliki organisasi lokal Sendi Aman Tiang Selamat di Maninjau. Namun setelah konflik internal Thawalib serta dinamika sosial pasca-gempa, ia bersama adiknya Yusuf Amrullah mengganti nama organisasi itu menjadi Muhammadiyah Grup Maninjau. Pada 25 Mei 1925, statusnya diakui sebagai cabang Muhammadiyah pertama di Sumatera Barat, bahkan salah satu yang pertama di luar Jawa.
Kemajuan berikutnya tidak lepas dari peran AR Sutan Mansur. Hamka menyebutnya sebagai figur yang lembut, fleksibel, dan ahli diplomasi yang kontras dengan gaya dakwah Haji Rasul yang tegas. AR Sutan Mansur berhasil merangkul ulama tradisional, saudagar, dan tokoh adat. Bahkan dua ulama besar Minangkabau, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Syekh Muhammad Zain Simabur, sempat bergabung dengan Muhammadiyah melalui pendekatannya. Dalam perspektif filsafat moral Aristoteles hal semacam ini adalah AR Sutan Mansur mewujudkan phronesis, yakni kebijaksanaan praktis yang memungkinkan sebuah gerakan bermetamorfosis dengan cara yang elegan dan inklusif.
Para saudagar Minang yang tergabung dalam Saudagar Verenehing juga berperan besar dalam menyediakan pendanaan bagi sekolah, pers, serta kegiatan dakwah. Keterlibatan saudagar menunjukkan bahwa Muhammadiyah Minangkabau sejak awal mengembangkan apa yang dalam etika Islam disebut collective fardhu kifayah, yakni tanggung jawab sosial yang diemban bersama. Dan hal ini tidak hanya tentang tanggung jawab sosial kemasyarakatan, tetapi juga tentang Pendidikan, Filantropi, dan Pembentukan Manusia Beradab. Etos pendidikan Muhammadiyah di Minangkabau adalah kelanjutan dari tradisi intelektual surau, tetapi dalam format modern. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Muhammadiyah mempraktikkan pendidikan sebagai pembebasan, sebagaimana teori Paulo Freire yang membangun kesadaran kritis dan memberi peluang mobilitas sosial. Di bidang sosial, rumah sakit, panti asuhan, layanan kebencanaan, dan program filantropi menjadi wujud nyata dari Islam rahmatan lil ‘alamin. Dalam kacamata etika Al-Farabi, tindakan-tindakan seperti ini merupakan tindakan memperkuat al-madinah al-fadhilah, yakni masyarakat utama yang bermoral.
Tantangan Abad Baru Dunia Digital dan Krisis Identitas
Memasuki abad kedua, tantangan Muhammadiyah Minangkabau semakin kompleks. Modernitas cair (liquid modernity) ala Bauman menghadirkan disrupsi nilai, krisis moral generasi muda, serta ketidakpastian identitas. Pendidikan dan dakwah digital perlu diperkuat tanpa mengorbankan adab dan kearifan lokal. Muhammadiyah harus mampu menciptakan ruang publik digital yang beradab sebagai penerus warisan Fort de Kock. Menata Masa Depan Sintesis Baru Minangkabau–Muhammadiyah dengan landasan sejarah, rasionalitas keagamaan, dan kearifan adat, Muhammadiyah Minangkabau memiliki modal besar untuk memimpin peradaban bangsa. Tugas abad berikutnya adalah menciptakan sintesis baru antara iman, ilmu, adat, dan teknologi. Visi masa depan mencakup:
Pertama, memperkuat pendidikan Islam berkemajuan. Kedua, menata etika digital generasi muda. Ketiga, merawat jaringan saudagar, filantropi, dan lembaga sosial. Keempat, membangun kader ulama-intelektual yang moderat dan kritis. Kelima, menafsir ulang hubungan adat dan syarak dalam horizon global.
Menutup refleksi ini, saya merasa penting untuk kembali menempatkan sejarah satu abad Muhammadiyah Minangkabau bukan sebagai monumen kebanggaan semata, melainkan sebagai cermin yang mengajak kita membaca diri sendiri. Sejarah sering menggoda kita untuk berhenti pada narasi kejayaan, membangun glorifikasi, dan menjadikan masa lalu sebagai tempat pelarian. Namun, seperti diingatkan oleh filsuf Paul Ricoeur, ingatan yang dewasa bukanlah ingatan yang memuja, melainkan ingatan yang merehabilitasi masa lalu untuk menata masa depan. Ingatan yang kritis, jujur, dan terbuka terhadap interpretasi baru. Spirit itu sesungguhnya sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh awal Muhammadiyah Minangkabau. Haji Rasul yang berani mengubah pendapat saat bertemu argumentasi lebih kuat. AR Sutan Mansur yang memilih diplomasi daripada pertentangan para saudagar yang bekerja tanpa ingin namanya ditinggikan dan para perempuan, seperti “Umi”, yang membuka pintu ruang publik meski tidak pernah dicatat sebagai pahlawan besar. Mereka tidak sibuk memuliakan diri atau organisasinya. Mereka bekerja melampaui dirinya.
Kadang saya membayangkan, seandainya mereka hidup hari ini, terutama di era kontemporer, algoritma, dan hiruk-pikuk identitas yang mungkin mereka justru akan meminta kita lebih berhati-hati. Agar kita tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai label kebanggaan semata, atau menjadikannya nostalgia romantik masa lampau. Karena pada hakikatnya, sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, “yang berat bukan mengenang perjalanan, tetapi melanjutkannya dengan keikhlasan.” Harapan saya untuk para generasi Muhammadiyah Minangkabau sangat sederhana namun fundamental: “jadilah pewaris yang kritis, bukan peniru yang pasif jadilah penggerak yang rendah hati, bukan pembawa slogan jadilah pencari kebenaran, bukan penjaga kepentingan.”
Menghormati sejarah bukan berarti membekukannya. Mencintai tradisi bukan berarti takut memperbaruinya. Berorganisasi bukan berarti mengikat diri pada formalisme, tetapi menghidupkan ruhnya. Di sinilah saya merasa pandangan Kant tentang keberanian berpikir menemukan relevansinya. Muhammadiyah tidak pernah lahir dari ketakutan, tetapi dari keberanian untuk melangkah mendahului zamannya. Kini, seratus tahun telah berlalu. Tetapi waktu tidak meminta kita mengulang masa lalu. Waktu meminta kita membuktikan apakah nilai-nilai itu masih hidup dalam diri kita, yakni “kejujuran intelektual, keberanian moral, kepedulian sosial, dan kesediaan untuk terus belajar”.
Jika empat hal itu tetap menyala dalam diri para generasi Muhammadiyah Minangkabau, maka sejarah satu abad yang kita peringati hari ini bukanlah puncak kejayaan, melainkan permulaan dari perjalanan yang lebih Panjang, yakni perjalanan menjadi manusia beriman, berilmu, dan bermanfaat di tengah dunia yang terus berubah. Dan mungkin, inilah cara paling jujur bagi kita untuk menghormati para pendahulu, bukan dengan menyanjung mereka, tetapi dengan melampaui mereka.