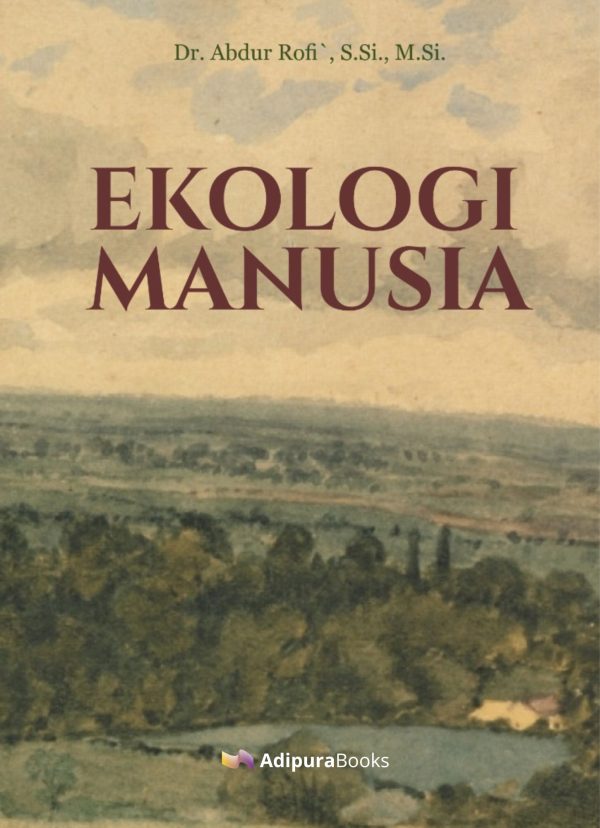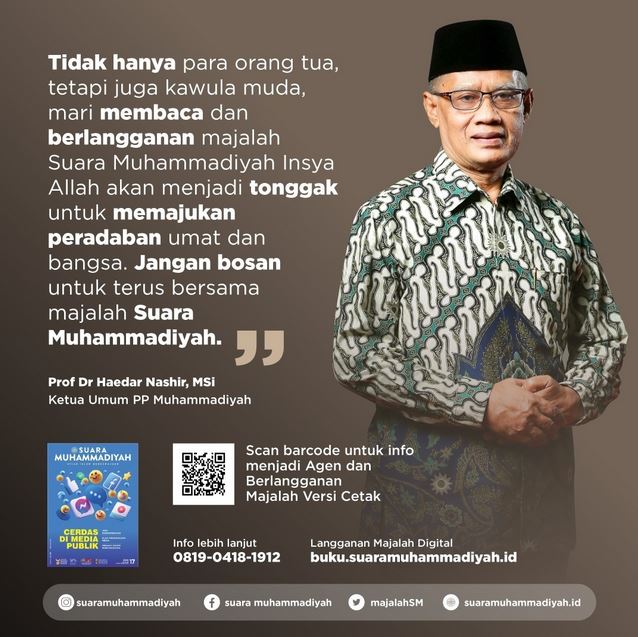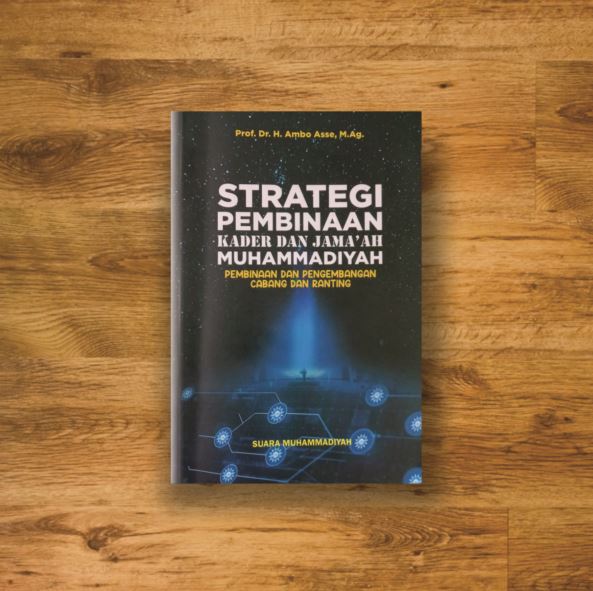Oleh: Muhammad Ridha Basri
Di berbagai belahan dunia, krisis lingkungan menjadi kenyataan sehari-hari yang semakin sering terjadi: banjir dan longsor, suhu ekstrem, ketahanan pangan yang rapuh, hingga keanekaragaman hayati yang menurun drastis. Kita sering menyalahkan “alam” yang berubah atau “bencana” yang datang tiba-tiba. Namun perspektif semacam ini justru menutupi kenyataan paling penting: krisis lingkungan adalah cermin dari cara manusia membangun kehidupan sosialnya. Alam tidak memburuk dengan sendirinya; manusialah yang gagal membaca pola interaksi antara dirinya dan ekosistem yang menopangnya.
Buku Ekologi Manusia (2025) karya almarhum Dr Abdur Rofi’ menawarkan sumbangan penting. Karya ini tampil sebagai sintesis utuh mengenai bagaimana manusia membentuk dan dibentuk oleh lingkungannya. Buku ini bukan sekadar rangkuman konsep ekologis, tetapi upaya serius untuk menghubungkan ilmu alam, ilmu sosial, budaya, dan agama dalam memahami masa depan peradaban manusia. Ia mengajak pembaca melihat lingkungan bukan sebagai objek luar, melainkan sebagai bagian menyatu dengan sistem sosial tempat manusia hidup sehari-hari.
Salah satu gagasan paling fundamental dalam buku ini adalah bahwa hubungan manusia–lingkungan bekerja melalui umpan balik (feedback). Ketika manusia mengubah lingkungan melalui pembangunan, teknologi, atau ekspansi kota, lingkungan akan merespons. Respons inilah yang kemudian kembali memengaruhi manusia, baik berupa kenyamanan maupun bencana.
Pola ini mungkin tampak abstrak, tetapi contoh konkretnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Urbanisasi cepat menyebabkan penyempitan ruang resapan air; lingkungan merespons dengan banjir yang semakin sering. Penggunaan pupuk kimia untuk mengejar produktivitas jangka pendek meningkatkan hasil panen; namun tanah merespons dengan kehilangan kesuburan, memaksa petani membeli pupuk lebih banyak, menurunkan pendapatan, dan memerangkap mereka dalam lingkaran kemiskinan. Apa yang tampak sebagai “masalah alam” sejatinya merupakan dampak sosial-ekologis yang terakumulasi.
Dengan memanfaatkan kerangka umpan balik positif dan negatif, Rofi’ menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipahami tanpa melihat struktur sosial, ekonomi politik, dan perubahan budaya yang menyertainya. Pendekatan ini relevan bagi publik Indonesia, yang sering memisahkan “alam” dari “masyarakat”, seolah keduanya dunia yang tidak saling berkaitan. Padahal, justru karena saling terkait, setiap kebijakan publik dalam bidang tata ruang, pertanian, transportasi, hingga industri, mempunyai konsekuensi ekologis jangka panjang.
Buku ini juga menyinggung salah satu tonggak sejarah yang paling memengaruhi Indonesia modern: Revolusi Hijau. Dengan teknik pertanian intensif, pupuk kimia, pestisida, dan varietas unggul, produksi pangan Indonesia melonjak, bahkan mencapai swasembada beras. Ini adalah contoh umpan balik positif: manusia berhasil memperluas daya dukung lingkungan untuk sementara waktu.
Namun keberhasilan itu mengandung paradoks. Tanah menjadi miskin hara, hama makin kebal, keragaman hayati turun, dan petani semakin bergantung pada input kimia serta benih, yang sebagian besar diproduksi korporasi besar. Inilah sisi negatif dari umpan balik: keberhasilan jangka pendek menciptakan kerentanan jangka panjang. Dengan kata lain, kita menambah kapasitas ekosistem secara artifisial tanpa memperhitungkan batas alaminya.
Rofi’ mengajak pembaca untuk memahami bahwa krisis lingkungan adalah krisis pengetahuan. Ketika kita hanya mengandalkan pendekatan teknis untuk memecahkan persoalan ekologis, kita kehilangan kemampuan mengenali batas-batas ekosistem. Pengetahuan lokal, yang selama berabad-abad menjaga keseimbangan alam, terpinggirkan oleh logika produksi massal.
Salah satu bagian paling menarik dalam buku ini adalah analisis tentang pergeseran ekosistem desa dan kota. Penulis menunjukkan bahwa desa bekerja sebagai sistem sosial-ekologi yang relatif stabil. Pola tanam, penggunaan lahan, dan pranata sosial seperti kerja gotong royong atau pengelolaan air tradisional menjadi mekanisme umpan balik negatif yang menjaga keseimbangan.
Namun pembangunan yang terlalu berorientasi pasar mengikis pranata ini. Desa kehilangan kearifan lokal, sementara kota berkembang melampaui daya dukungnya. Kota tumbuh pesat, tetapi kehilangan ruang hijau, ruang air, dan hubungan ekologis yang menjaga kualitas hidup. Rumah padat, industri tinggi, kendaraan berlimpah, tetapi fondasi ekologisnya rapuh. Akibatnya, persoalan kota tidak pernah selesai: sampah, banjir, polusi, dan ketimpangan ruang.
Penulis dengan tepat mengingatkan bahwa kota bukan sekadar tumpukan gedung, dan desa bukan sekadar kawasan produksi pangan. Keduanya merupakan bagian dari satu lanskap besar yang saling mempengaruhi. Ketika desa rusak, kota pun ikut mengalami krisis; ketika kota tidak ramah ekologis, desa menerima limpahan bebannya.
Buku ini juga memasukkan perspektif agama dalam diskusi ekologi. Banyak analisis lingkungan berhenti pada data ilmiah dan kebijakan teknis. Padahal, menurut penulis, persoalan ekologi pada dasarnya adalah persoalan nilai dan etika. Agama dipandang memiliki potensi besar untuk mengembalikan kesadaran ekologis yang hilang. Islam, misalnya, memiliki tradisi fikih lingkungan (fikih al-bi’ah) atau konsep ekoteologi yang belakangan gencar digelorakan oleh Kementerian Agama. Prinsip khilafah dan amanah menjadi fondasi penting untuk membangun habitus ekologis dalam masyarakat.
Dengan mengangkat studi kasus fikih ekologi di Indonesia, penulis menunjukkan bahwa etika agama bukan ide abstrak, tetapi praktik nyata di banyak komunitas. Sayangnya, dimensi moral ini jarang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan modern cenderung melihat manusia sebagai konsumen, bukan penjaga kehidupan; melihat alam sebagai sumber daya, bukan rumah bersama. Di sinilah penulis menyuarakan kritik yang relevan: tanpa etika, pembangunan akan kehilangan arah.
Buku ini juga membahas dinamika penduduk sebagai faktor kunci ekologi manusia. Dengan kerangka transisi demografi, penulis menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi bukan hanya soal angka kelahiran dan kematian, tetapi akibat kombinasi faktor kesehatan, teknologi, urbanisasi, dan pilihan hidup masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang menghasilkan tekanan besar pada ekosistem: kebutuhan pangan meningkat, air bersih menurun, ruang hijau hilang, dan sampah meningkat. Dan pada titik tertentu, kapasitas bumi tidak lagi mampu menopang beban tersebut. Bumi memiliki batas fisik, sosial, dan etis yang tidak dapat dilanggar.
Yang membuat buku Ekologi Manusia istimewa bukan hanya kelengkapan teorinya, tetapi juga nada reflektif yang membangun kesadaran moral pembaca. Dalam salah satu bagian, penulis menegaskan bahwa merusak lingkungan sama saja dengan mengkhianati tanggung jawab kepada sesama manusia dan kepada Tuhan. Pandangan ini penting ditonjolkan di tengah dominasi paradigma pembangunan yang hanya menilai kemajuan dari pertumbuhan ekonomi. Penulis menunjukkan bahwa pembangunan sejatinya harus menyeimbangkan tiga komponen: ekonomi, sosial, dan ekologi. Ketika salah satu dimensi diabaikan, kesejahteraan akan rapuh.
Akhirnya, membaca buku Ekologi Manusia karya Abdur Rofi’ terasa seperti membuka peta besar tentang bagaimana kehidupan bekerja dan bagaimana ia bisa runtuh jika manusia lalai. Perubahan ekologis tidak mungkin terjadi tanpa perubahan manusia. Dengan argumentasi ilmiah dan alasan moral yang kokoh, buku ini menjadi warisan intelektual yang penting bagi masa depan bumi.
Judul : Ekologi Manusia
Penulis : Dr. Abdur Rofi`, S.Si., M.Si.
Ukuran : 14.8 X 21 cm
Halaman : 153
Edisi : Pertama 2025
ISBN : 978-623-88144-7-3
Muhammad Ridha Basri, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.