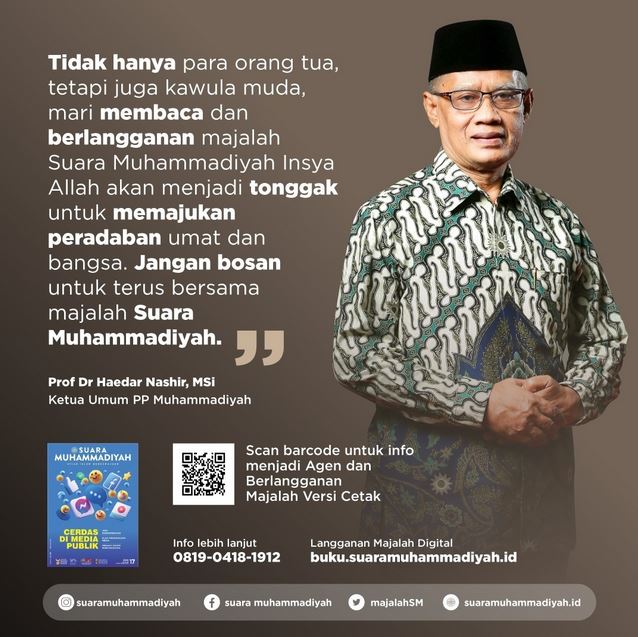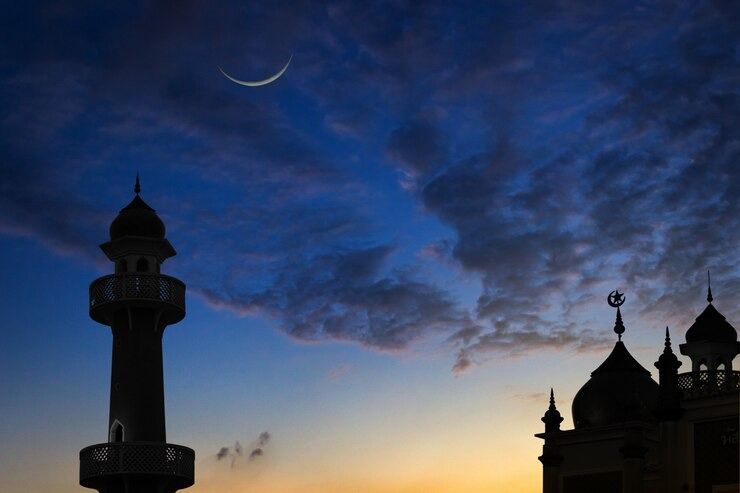Demokrasi dan Pembangunan
Oleh: Badru Rohman, Advokat dan Pemerhati Sosial
Diskursus antara das sollen dan das sein dalam konteks demokrasi dan pembangunan merupakan kata kunci untuk mengatasi kesenjangan. Das sollen merujuk pada norma dan tujuan ideal, sementara das sein adalah realita yang terjadi. Memahami dan menjembatani kesenjangan ini penting untuk menciptakan masyarakat lebih adil dan setara.
Secara harfiyah, demokrasi dapat dimengerti sebagai sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elit yang memerintah. Demokrasi juga dipahami sebagai polity di mana semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berserikat, punya hak sama di depan hukum dan bebas menjalankan agama yang dipeluknya.
Demokrasi juga sering dimengerti sebagai pengakuan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi dimengerti sebagai government of the people, by the people and for the people. Dengan demikian, demokrasi memungkinkan tersalurnya aspirasi dan partisipasi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam ikut membuat keputusan atau kebijaksanaan.
Demokrasi juga berarti mentolerir adanya perbedaan pendapat atau dalam pengertian tertentu dengan konflik. Konflik di sini, tentunya bukan konflik yang merusak sistem politik yang sedang berlangsung, Samuel Huntington menyoroti demokrasi dari satu sisi, yaitu pelaksanaan pemilu. Suatu sistem itu demokratis jika para elite pemerintahan diseleksi secara periodik melalui pemilu yang jujur.
Namun demikian, jika mencermati secara seksama, realita praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia akhir akhir ini, menggambarkan ketaknyambungan antara demokrasi dalam pengertian yang seharusnya (das sollen) dengan demokrasi yang pengertian senyatanya (das sein). Melansir warta ekonomi.co.id tertanggal 27/3/2024, pemilu 2024 sarat dengan distorsi atau sejumlah penyimpangan.
Peneliti utama politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro dalam diskusi daring “Pilpres 2024 dan Pertaruhan Mahkamah Konstitusi”, di kanal Youtube Forum Insan Cita (25/3/24), distorsi bukan hanya soal etika, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum. Ada pelanggaran dan pelanggarannya bukan hanya etika tapi juga hukum. Diantaranya pencalonan presiden dan wakil presiden diwarnai kontroversi khususnya terkait batas umur calon.
Terlepas bicara sah tidaknya menurut hukum, Prabowo setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, dalam pidatonya menyebutkan ajakan untuk bersama-sama membangun bangsa dan menghilangkan perbedaan. Tafsir terkait dengan pidato tersebut memiliki dua makna sekaligus. Pertama, mengajak semua kekuatan politik untuk bergabung guna memperkuat barisan koalisi pemerintahannya.
Kedua, pihak yang kalah dalam pilpres 2024 tetap di luar dan tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan, tetapi dimohon untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan selama Prabowo-Gibran memimpin negara ini dalam lima tahun ke depan. Meskipun perpolitikan di Indonesia tidak dikenal istilah oposisi, akan tetapi dalam setiap praktik berbangsa dan bernegara tetap dibutuhkan adanya penyeimbang untuk check and balance pemerintahan.
Memasuki tahun 2025 kira kira pada bulan ke dua, unjuk rasa dengan tanda pagar #Indonesia Gelap menderas dalam beberapa pekan terakhir. Mahasiswa di berbagai daerah mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat. Mereka juga terpicu oleh pidato Presiden yang dianggap menghina para pengkritisnya. Pemerintah dinilai makin otoriter dan anti kritik.
Demikian juga tagar #Kabur aja dulu, yang muncul sejak 2023 menguat karena ketidakpuasan terhadap pemerintah terkait percakapan di media sosial tentang tagar ini diawali oleh diskusi terkait insentif bagi pekerja IT jauh lebih besar di luar negeri ketimbang di Indonesia. Inilah salah satu bentuk kekecewaan masyarakat kepada pemerintah yang tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan hidup.
Tulisan ini berusaha untuk membahas tentang demokrasi dan pembangunan Indonesia antara Das Sollen dan Das Sein. Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dan apa yang sebenarnya terjadi (das sein) dalam sistem demokrasi dan pembangunan Indonesia.
Politik Tanpa Nilai
Dalam konteks Indonesia, para pemikir di seputar jelang kemerdekaan (persidangan BPUPKI), yang kemudian menghasilkan rumusan Pancasila adalah produk dari politik nilai. Sila-sila dalam Pancasila sarat dengan nilai-nilai agung dan mulia, sebagaimana ditawarkan Plato maupun al-Farabi. Namun demikian, terlebih era politik liberal, politik nilai nyaris menjadi hal yang sangat asing.
Politik saat ini telah benar-benar dipahami hanya dalam pengertian yang pragmatis, dimana politik hanya dimengerti sebagai perebutan kekuasaan dan kepentingan. Penulis menyadari bahwa politik itu memang (diantaranya) berbicara soal bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan. Tak ada lawan atau kawan yang abadi. Abadi itu kepentingan, ini ungkapan yang kerap kita dengar.
Mencermati praktik politik di Indonesia, praktis yang tampil dan menjadi mainstream adalah politik tanpa nilai. Politik yang semata bicara soal kekuasaan dan kepentingan, sementara politik dalam pengertian nilai dimarjinalkan. Produk dari praktik politik yang seperti saat ini, betapa bobroknya kehidupan politik saat ini. Nyaris tanpa nilai, tak ada komitmen, tak ada kepercayaan dan tak ada integritas.
Melanggar komitmen, melanggar kepercayaan, tipu-tipu, berkhianat, mengorbankan atau menikam kawan sendiri dan apalagi lawan, seakan menjadi sebuah keniscayaan dalam praktik politik saat ini. Dalam sejarah pemilu sejak tahun 1955 sampai detik ini, rasanya baru kali ini terjadi pertarungan yang berhasil menciptakan polarisasi secara tajam, ekstrem. Bisa jadi negaralah yang sejatinya berada di balik polarisasi ideologis ini.
Demokrasi dan partai politik (parpol) tidak mungkin dipisahkan. Namun munculnya sekian banyak parpol dengan visi dan identitas yang tidak jelas, justru menggerogoti substansi dan cita luhur demokrasi, yakni membangun pemerintahan berkualitas demi memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat.
Keberadaan parpol sangat strategis untuk menjembatan kepentingan pemerintah (negara) dan rakyat. Rakyat sebagai ibu kandung negara mutlak memerlukan pemerintahan yang mampu melindungi, menyejahterakan, dan memajukan Pendidikan mereka. Pendek kata, pemerintah adalah pelindung dan pelayan rakyat.
Namun demikian, kali ini, posisi parpol sebagai jembatan kepentingan negara dan rakyat mulai dipertanyakan, bagaimana tidak, pada praktiknya parpol lebih merupakan pelembagaan formal dari sekelompok massa yang tidak memiliki kualifikasi untuk membangun birokrasi dan kultur pemerintahan yang andal. Terlebih ketika negara dalam kondisi sangat rapuh dan bebannya sangat berat, seperti yang dihadapi saat ini.
Apakah sekian banyak parpol yang ada, memiliki program visi dan kader-kader andal yang bisa menyelamatkan bangsa dari carut marut negeri ? Apakah parpol memiliki agenda konkret dan rasional untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat ? Ataukah justru carut marutnya negeri sebagai actor adalah parpol itu sendiri ? Saat ini kita merasakan adanya krisis kepercayaan rakyat, baik kepada parpol figur, maupun lembaga negara, sejak dari DPR, kejaksaan hingga departemen.
Pancasila sebagai ideologi negara, bak sebuah iklan. Lazimnya iklan, rasanya terlalu banyak bintang iklan yang hanya pandai mengiklankan produk yang dibintanginya tanpa berusaha untuk memakai produknya. Kalaupun terpaksa memakai produknya, biasanya hanya sebatas kepatutan selama masa kontrak sebagai bintang iklan. Selebihnya mencampakkan begitu saja.
Suasana ideologis di era orde baru terulang kembali pada era ini. Bahkan kondisinya jauh lebih buruk. Jika dahulu ketegangan di era Orde Baru adalah murni ketegangan ideologis antara state dengan civil society, seperti Forum Demokrasi dan Petisi 50. Sementara ketegangan yang terjadi saat ini sengaja “diciptakan” atau ada semacam ideological engineering, seolah-olah terjadi ketegangan ideologis antara kelompok Pancasilais dengan yang tertuduh anti Pancasilais.
Jika dicermati betul secara mendalam, sejatinya ideologis yang terjadi saat ini motifnya bukan (semata) ideologis sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, tapi ada motif-motif ekonomi, dimana ada kekuatan ekonomi raksasa yang selama ini sudah menguasai perekonomian kita yang mencoba melakukan cengkeraman lebih dalam lagi dengan cara memanfaatkan isu-isu ideologis.
Ketika elite negeri ini tak berusaha serius menghadirkan Pancasila sebagaimana spirit ketika disepakati sebagai ideologi negara, tanggal 18 Agustus 1945, tentu dengan mengabaikan gentlemen agreement tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta, maka selamanya Pancasila tak akan pernah berarti apapun bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila selamanya hanya akan sebatas jargon untuk adu domba dan polarisasi ideologis.
Ketika politik dalam konteks pemisahan maupun pembagian kekuasaan (separation of distribution of power) tidak mampu lagi untuk dijalankan dengan baik oleh Lembaga-lembaga politik formal, maka ormas keagamaan dan elemen masyarakat lainnya sebagai bagian kekuatan politik penting untuk mengambil alih kontrol politik tersebut. Hanya langkah ini yang dinilai baik, konstitusional, dan efektif untuk mengontrol politik yang menyimpang.
Sebelum terselenggaranya pemilu 2024, melansir kompas.com tertanggal 09/02/2024 dengan judul Polri Dianggap Tak Bersikap Dewasa, Minta Rektor Apresiasi Jokowi, oleh Aryo Putranto Saptohutomo, berpendapat bahwa langkah Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi buat meredam potensi konflik dengan meminta kalangan akademisi membuat video testimoni tentang pemerintahan Jokowi dinilai sebagai sikap tidak dewasa.
Melansir BBC.com tertanggal 08/02/2024 dengan judul sejumlah universitas diminta membuat video apresiasi,.. Pakar Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan menyebut tindakan polisi tersebut jelas ingin menggembosi sikap kritis sivitas akademika. Polisi malah nyata-nyata menunjukkan ketidaknetralan dengan membuat siasat meminta sejumlah petinggi kampus membuat video bertujuan mengapresiasi kinerja Jokowi.
Namun demikian, ditengah kuatnya hegemoni negara yang dipersenjatai (weaponized state) dengan mobilisasi kekuatan tantara, polisi, birokrasi, universitas, dan bahkan ormas keagamaan. Muncullah gerakan yang menciptakan ruang untuk bergerak dan melawan berbagai praktik ketidakadilan dalam kebijakan publik yang mencekik hidup rakyat dengan sebuah nama Indonesia gelap.
Ketika MK memutuskan pemisahan pemilu nasional dan pilkada dalam putusan nomor 135/PUU-XXII/2024, menjadi perhatian semua pihak. Ketua DPR Puan Maharani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu telah menyalahi UUD 1945. Dalam hal ini Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.
MK tidak berpendapat lain, putusan MK 135/2024 tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 55/PUU-XVII/2019. Menurut Enny, dalam putusan tersebut MK telah menegaskan model keserentakan pemilu yang dapat ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Termasuk salah satu modelnya adalah memisahkan pemilu nasional dan pemilu local, ujarnya. Hal demikian menunjukkan bahwa pemilu belum menjadi sarana kedaulatan rakyat, akan tetapi pemilu hanya sekedar instrument untuk melanggengkan kekuasaan.
Pembangunan: Perspektif Optimisme dan Pesimisme
Jargon Indonesia Gelap bukan sekedar slogan, melainkan cerminan realitas yang harus disikapi dengan serius. Kehancuran lingkungan akibat kebijakan pro elit dapat dianalisa dalam konteks oligarki, sebagaimana dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarchy. Menurut Winters, mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi akan menggunakan politik untuk mempertahankan dan memperluas dominasi mereka. Hal ini terlihat dalam komposisi pemerintahan dan legislative yang didominasi oleh pengusaha di sector ekstraktif.
Istilah Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk kekhawatiran dan kritik terhadap pembangunan Indonesia, memunculkan perdebatan antara pandangan optimis dan pesimis. Kelompok yang pesimis menyoroti ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang masih terjadi. Sementara yang optimis melihat kemajuan dan potensi Indonesia.
Istilah “Indonesia gelap” dalam konteks konotasi Bahasa komunikasi dapat memiliki beberapa maka, tergantung pada bagaimana kata “gelap” itu digunakan. Secara denotasi, “gelap” berarti tidak ada cahaya. Namun dalam Bahasa kiasan, “gelap” berarti bisa merujuk pada berbagai hal negatif. Misalnya, “Indonesia Gelap” bisa merujuk pada situasi sosial, ekonomi, atau politik yang suram, penuh masalah, atau kurang baik.
Ada beberapa kemungkinan dari pandangan pesimisme tentang memaknai konotasi istilah Indonesia gelap, Pertama, Kondisi sosial atau ekonomi yang buruk, kata gelap dapat melambangkan kemiskinan, ketidakadilan, atau kurangnya kesempatan bagi masyarakat. Kedua, situasi politik yang tidak stabil, kata gelap bisa mengacu pada korupsi, konflik, atau kurangnya transparansi dalam pemerintahan.
Ketiga, masa depan yang tidak pasti, kata gelap bisa menggambarkan ketidakpastian tentang masa depan Indonesia, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun lingkungan. Keempat, perasaan putus asa atau pesimis, secara emosional, kata gelap bisa mencerminkan perasaan putus asa atau pesimis terhadap kondisi negara. Maka penting untuk memahami konteks fenomena baru, membutuhkan penamaan baru, agar dapat diidentifikasi, dipahami, dan dibahas secara efektif. Sehingga dipilihlah nama baru itu dengan Indonesia gelap.
Melansir Antara 21/07/2025 dengan judul Isu Indonesia Gelap merupakan rekayasa dari koruptor. Presiden RI Prabowo Subianto saat memberi sambutan pada acara penutupan kongras PSI di Surakarta, Minggu (20/7) menyebutkan bahwa isu dan tagar Indonesia Gelap yang sempat ramai di media sosial merupakan rekayasa yang dibuat oleh koruptor dengan membayar buzzer sehingga berhasil membuat gaduh masyarakat.
Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme, saya geleng-geleng kepala, ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme, Indonesia gelap, kata Prabowo yang juga hadir sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Uraian alenia terakhir tersebut di atas, terlepas membahas tentang penggunaan Bahasa komunikasi Presiden Prabowo, tentu mengarah pada optimisme pembangunan, bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia Cerah, masa depan Indonesia cerah. Meskipun ada tantangan, optimisme ini didorong oleh keyakinan akan kemampuang bangsa untuk mengatasi dan meraih kemajuan.
Melansir mpr.gp.id dan mengutip Rmol.id (20/02/25) Waka MPR : Optimisme akan membuat bangsa cerah dan maju. Membangun dan berkontribusi untuk Indonesia sebaiknya dimulai dengan optimisme. Terjebak pada pesimisme, justru akan membuat masa depan Indonesia menjadi gelap. Begitu disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons gerakan Indonesia Gelap.
Ada beberapa kemungkinan pandangan optimisme terhadap masa depan Indonesia, khususnya dalam pembangunan, diantaranya: Pertama, potensi sumber daya alam dan manusia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar, jika dikelola dengan baik dapat menjadi modal utama untuk pembangunan. Kedua, pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi fokus utama, dengan dukungan terhadap UMKM dan sektor strategis seperti industri kreatif dan teknologi. Ketiga, Pendidikan, peningkatan kualitas Pendidikan dan pengembangan karakter kebangsaan pada generasi muda dianggap penting untuk membentuk fondasi yang kuat bagi masa depan. Keempat, Inovasi dan Teknologi.
Kemajuan teknologi dan inovasi menjadi pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Kelima, kerjasama dan rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan yang kuat, kerja keras, dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia.
Meskipun berpandangan optimisme, tentu ada tantangan dan hambatan, diantaranya : Pertama, Resiko Ekonomi, perlu di ingat bahwa faktor resiko bisa muncul kapan saja, sehingga sistem proteksi asset dan kebijakan yang bijaksana sangat diperlukan. Kedua, pemerataan pembangunan, pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia sejak dahulu menjadi tantangan, termasuk pemerataan akses Pendidikan dan teknologi.
Ketiga, Pendidikan karakter. Pendidikan tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Dan keempat, infrastruktur digital. Pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat perlu terus didorong untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam era revolusi industri.
Demokrasi dan Pembangunan : Antara Das Sollen dan Das Sein
Dikotomi “Indonesia Gelap” dan “Indonesia Terang” sebagai diskursus adalah tidak relevan, akan tetapi yang lebih relevan adalah perbedaan antara “das sollen” (seharusnya) dan “das sein” (kenyataan) dalam konteks demokrasi dan pembangunan. Dikotomi :Indonesia Gelap” dan “Indonesia Terang” mengindikasikan bahwa pembagian dua kubu yang saling bertentangan dan tidak akurat. Karena cenderung menyederhanakan masalah kompleks dan memicu sekedar untuk polarisasi.
Dalam konteks demokrasi, diskursus antara das sollen dan das sein sangatlah relevan, das sollen merujuk pada norma-norma ideal dalam demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi, dan kesetaraan. Sementara das sein adalah praktik demokrasi yang seringkali menyimpang dari ideal tersebut, seperti korupsi, ketidakadilan, dan oligarki.
Dalam konteks pembangunan, das sollen mencakup berbagai aspek seperti tujuan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka Panjang, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan berbagai target yang ingin dicapai. Misalnya, tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial dan lain-lain.
Sedangkan das sein adalah realitas yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Ini mencakup pelaksanaan kebijakan, implementasi program, perilaku masyarakat, dan dampak yang dihasilkan dari pembangunan. Misalnya, meskipun ada kebijakan tentang perlindungan lingkungan, kenyataannya masih banyak terjadi pencemaran lingkungan.
Kesenjangan antara das sollen dan das sein, seringkali terjadi karena berbagai faktor, seperti : Pertama, keterbatasan sumber daya, terkadang sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk mencapai tujuan pembangunan yang ideal. Kedua, kurangnya implementasi. Meskipun ada peraturan dan kebijakan yang baik, implementasinya bisa terhambat oleh berbagai factor, termasuk birokrasi, korupsi, atau kurangnya kesadaran masyarakat.
Ketiga, perbedaan kepentingan, kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan bisa berbeda-beda, sehingga terjadi benturan kepentingan yang menghambat pencapaian tujuan. Keempat, perubahan kondisi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berubah-ubah juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan menyebabkan kesenjangan dengan das sollen.
Pentingnya mengatasi kesenjangan
Mengatasi kesenjangan antara das sollen dan das sein sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi dan pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan antara lain : Pertama, memperbaiki peraturan dan kebijakan. Memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang ada relevan dengan kondisi nyata dan mudah diimplementasikan.
Kedua, meningkatkan implementasi. Memperbaiki system birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memerangi korupsi untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Terkait tujuan tujuan demokrasi dan pembangunan dan hak-hak mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi an pembangunan. Dan Keempat, memperkuat penegakan hukum.
Perbedaan antara “das sollen” dan “das sein” dalam konteks demokrasi dan pembangunan lebih relevan karena memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi dan pembangunan yang berkualitas. Dengan demikian, penulis mengajak untuk melihat masalah-masalah yang ada dalam konteks yang lebih realistis, dari pada terjebak dalam dikotomi yang menyederhanakan masalah.