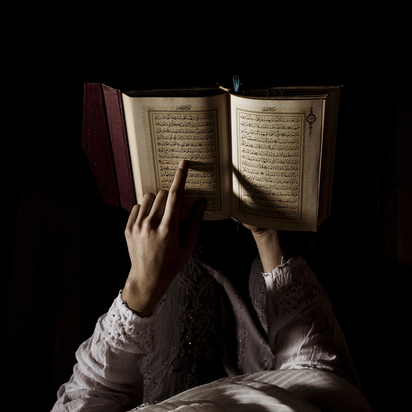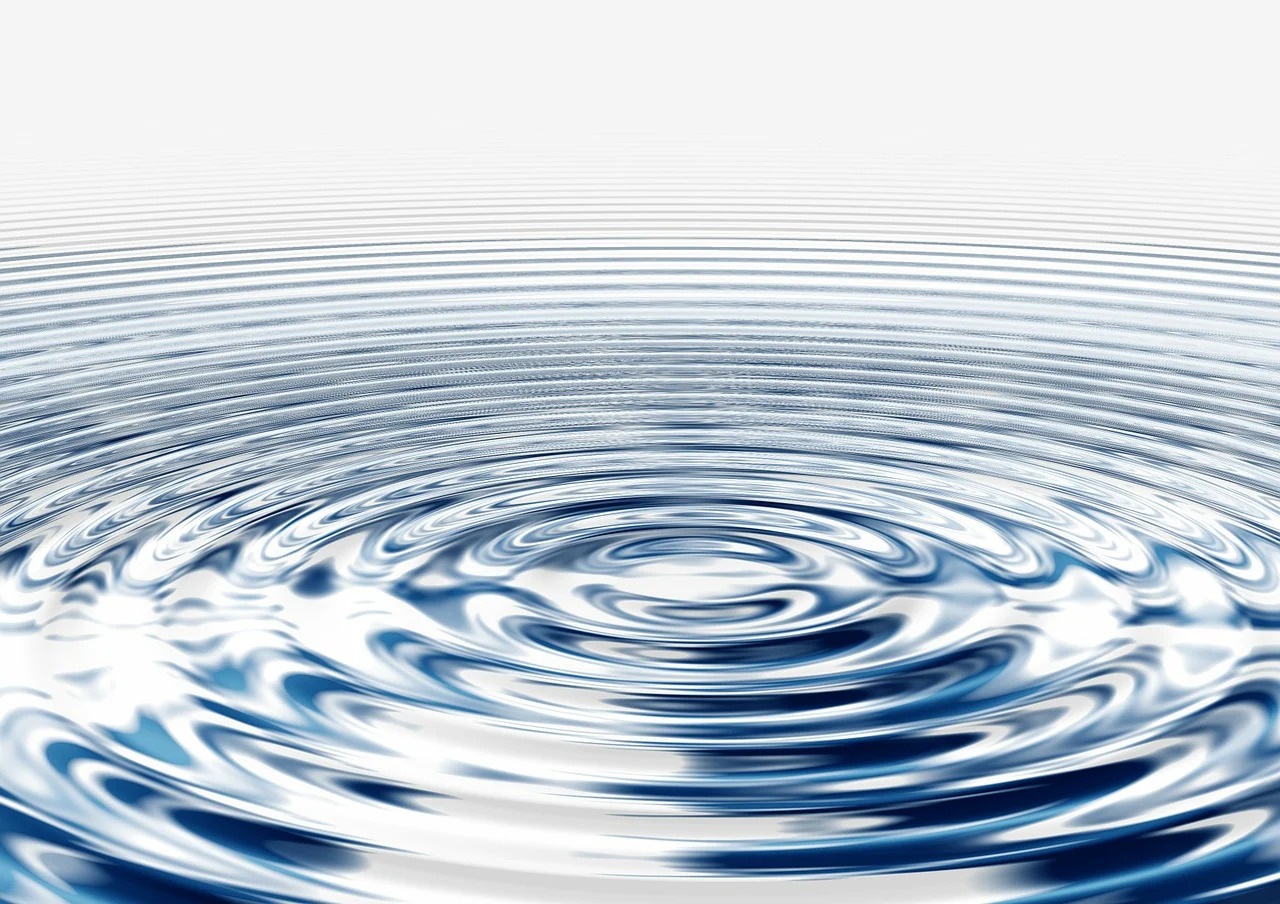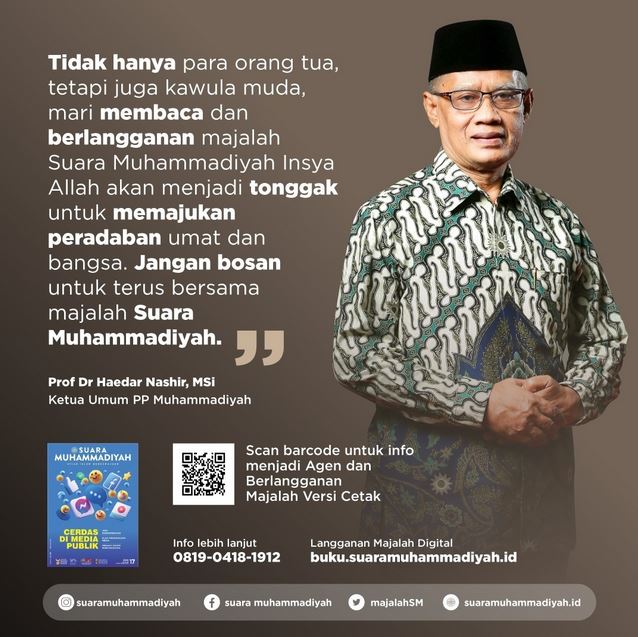Cahaya Hidayah dan Krisis Akhlak Digital: Tafsir Filosofis–Sufistik atas QS. al-Fātiḥah: 6 dan Relevansinya dengan Pergaulan Masyarakat di Dunia Maya
Oleh: Piet Hizbullah Khaidir, Ketua STIQSI Lamongan; Sekretaris PDM Lamongan; dan Ketua Divisi Kaderisasi dan Publikasi MTT PWM Jawa Timur
Dunia digital hadir sebagai ruang hidup baru bagi manusia modern. Ia membentuk cara kita bekerja, berinteraksi, berfikir, bahkan menentukan nilai-nilai moral yang diikuti masyarakat. Arus informasi bergerak begitu cepat sehingga batas antara fakta dan opini, antara etika dan euforia, semakin kabur. Tidak berlebihan bila banyak pengamat menyebut masa kini sebagai era krisis akhlak digital, ketika manusia tertarik pada sensasi tetapi abai pada substansi, terhubung tetapi kesepian, cerdas secara teknis tetapi kerdil secara etik.
Di tengah kegaduhan semacam itu, ajaran Islam menawarkan sebuah cahaya yang bersifat transhistoris: hidayah. Dalam QS. al-Fātiḥah [1]: 6, doa ihdina al-ṣirāṭ al-mustaqīm menjadi inti seluruh permohonan manusia kepada Allah. Ayat ini bukan sekadar laku ibadah, tetapi model kesadaran spiritual yang menentukan kualitas akhlak seseorang. Namun bagaimana makna hidayah dapat dibaca kembali dalam konteks krisis akhlak digital? Bagaimana tradisi filosofis–sufistik membantu merumuskan ulang relevansinya bagi pergaulan masyarakat di dunia maya?
Dimensi Makna Konseptual Hidayah
Para ulama klasik memahami hidayah sebagai petunjuk Ilahi yang bekerja melalui dua dimensi: aktif (hudā) dan pasif (hidayah). Dalam banyak ayat seperti hudan li al-muttaqīn (QS. Al-Baqarah [2]: 2, petunjuk bersifat aktif—artinya manusia dituntut berilmu, memahami wahyu, dan mengamalkannya secara konsisten sehingga menjadi akhlak yang mengakar. Petunjuk aktif menuntut disiplin intelektual dan asketisme moral.
Sebaliknya, hidayah pasif—seperti dalam innaka lā tahdī man aḥbabta walākinna Allāha yahdī man yashā’ wa huwa a’lam bi al-muhtadin (QS. Al-Qasas [28]: 56—merujuk pada cahaya iman yang dianugerahkan Allah kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dan sebab Dia lebih mengetahui siapa yang layak memperoleh petunjuk. Di sini manusia tunduk, memohon, dan menyadari keterbatasannya. Keduanya membentuk relasi antara ikhtiar manusia dan anugerah Tuhan.
Dalam dunia digital yang serba impulsif, konsep ini mengingatkan bahwa akhlak bukan “produk instan” dari tren sosial, tetapi jalan panjang yang memadukan upaya intelektual, pengendalian diri, dan kesadaran spiritual. Dalam konteks ini, Fakhr al-Din al-Razi dalam kitab ‘Aja’ib al-Qur’an, ketika menjelaskan inti petunjuk dalam rahasia kalimat tawhid dan istighfar, menjelaskan bahwa gerak petunjuk itu dimulai dari ilmu yang mendalam dan penuh penghayatan (gerak intelektualitas), lalu dilanjutkan dengan akhlak yang dipraktekkan dengan penuh pengakuan akan kelemahan dan kesempurnaan (gerak etik). Dengan kata lain, gerak intelektualitas harus mendahului gerak etis, namun harus berjalan seiring bahkan bersamaan. Demikianlah ketika, mufassir yang filsuf ini menjelaskan QS. Muhammad [47]: 19.
Dua konsep turunannya, rushd dan tawfīq, memperjelas operasionalisasi hidayah. Rushd bermakna hikmah praktis yang membuat seseorang mampu memilih tindakan tepat pada situasi rumit. Ia sejalan dengan practical wisdom Aristoteles. Sedangkan tawfīq adalah kesesuaian antara kehendak manusia dengan kehendak Ilahi—kekuatan batin untuk konsisten dalam kebaikan.
Dalam era digital, rushd menjadi benteng dari informasi menyesatkan, polarisasi algoritma, dan budaya viralitas. Sementara tawfīq menjadi pagar spiritual agar seseorang menjaga integritas meski ruang digital memungkinkan anonimitas dan kebebasan tanpa batas.
Rahasia Dhamīr Nā dan Makna al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm: Fondasi Etika Kolektif Dunia Maya
Kata ihdinā (“tunjukkanlah kami”) mengandung dhamīr nā yang menunjukkan dimensi kolektif. Menurut al-Ṭabarī, doa ini menunjukkan bahwa keselamatan spiritual tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial. Al-Zamakhsharī menegaskan bahwa manusia hanya dapat stabil di jalan lurus jika komunitas di sekitarnya turut terarah.
Al-Rāzī membaca dhamīr ini sebagai isyarat bahwa manusia adalah makhluk relasional; akhlak tidak lahir dari isolasi. Ibn ‘Arabī memaknainya lebih mendalam: “kami” adalah jejaring eksistensial makhluk yang saling mempengaruhi. Seseorang tidak dapat meminta kebaikan bagi dirinya tanpa memikirkan orang lain.
Dalam konteks digital, dhamīr ini bermakna bahwa setiap jejak digital memiliki dampak luas. Memohon ihdinā berarti memohon kemampuan menciptakan ekosistem digital yang sehat, bukan hanya perilaku personal yang terjaga.
Bagian akhir ayat—al-ṣirāṭ al-mustaqīm—adalah bentuk hasil yang diharapkan dari permohonan hidayah. Keempat mufasir besar memberikan penjelasan yang membuka cakrawala baru:
1. Fakhr al-Dīn al-Rāzī
Al-Rāzī menafsirkan al-ṣirāṭ al-mustaqīm sebagai “jalan intelektual dan moral yang paling sempurna.” Baginya, jalan lurus adalah integrasi antara benarnya pemahaman dan benarnya tindakan. Tidak cukup seseorang mengetahui yang benar; ia harus menghidupkannya dalam akhlak.
Relevansi digital: Al-Rāzī mengajarkan bahwa literasi digital harus disertai literasi moral. Pengetahuan tanpa etika hanya melahirkan kebisingan intelektual. Sebaliknya, etika tanpa ilmu pengetahuan hanya menghantarkan seseorang kepada perilaku tanpa dasar dan panduan yang jelas.
2. Ibn ‘Arabī
Menurut Ibn ‘Arabī, al-ṣirāṭ al-mustaqīm adalah “jalan kesadaran” yang menghubungkan manusia dengan sumber hakikat. Dalam pandangan mistiknya, jalan lurus adalah keseimbangan antara lahir dan batin, antara realitas material dan realitas spiritual.
Relevansi digital: Dunia digital menciptakan keterputusan antara identitas maya dan identitas nyata. Jalan lurus mengajarkan kesatuan diri—kejujuran dalam persona digital seperti kejujuran dalam kehidupan nyata. Sebuah panduan agar manusia dalam pergaulan digital menghilangkan kehaluan dan hipokrisi.
3. Ṭabāṭabā’ī
Ṭabāṭabā’ī melihat jalan lurus sebagai “jalan pengetahuan dan amal yang membawa pada kesempurnaan manusia.” Ia menekankan bahwa jalan ini bersifat progresif—manusia bertumbuh setahap demi setahap menuju kualitas akhlak tertinggi.
Relevansi digital: Dalam budaya instan, Ṭabāṭabā’ī mengingatkan bahwa akhlak digital adalah proses jangka panjang—bukan popularitas sesaat. Kesempurnaan akhlak seseorang berada pada kesinambungan perilakunya dalam berlaku bajik, namun tidak boleh merasa paling bajik, apalagi menganggap orang lain tidak lebih bajik daripada dirinya.
4. al-Sha‘rāwī
Al-Sha‘rāwī menekankan aspek praktis: jalan lurus adalah “jalan yang tidak menyimpang dari kebenaran, meski dunia menawarkan banyak jalan alternatif.” Jalan lurus adalah pilihan yang konsisten.
Relevansi digital: Dalam dunia penuh godaan konten merusak, jalan lurus berarti kemampuan memilah, menahan diri, dan memilih yang bermanfaat meskipun tidak populer.
Dari keempat mufassir di atas, al-ṣirāṭ al-mustaqīm dapat dipahami sebagai: jalan intelektual, jalan moral, jalan spiritual, dan jalan praktik sehari-hari. Empat jalan lurus ini adalah kerangka hidup yang stabil di tengah perubahan zaman, di tengah pergaulan masyarakat digital.
Krisis Akhlak Digital: Ketika Hidayah Menjadi Kebutuhan Mendesak
Krisis akhlak digital timbul dari derasnya misinformasi, budaya penghinaan, normalisasi kekerasan verbal, pencarian validasi tanpa batas, dan hilangnya orientasi moral akibat dominasi algoritma. Dalam situasi ini, hidayah dan pemaknaan al-ṣirāṭ al-mustaqīm menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.
Keduanya memberi kerangka epistemik untuk memilah informasi, menjadi kompas moral dalam interaksi digital, menguatkan kesehatan spiritual di tengah racun informasi, dan membangun tanggung jawab sosial melalui kesadaran bahwa jejak digital adalah bagian dari doa “kami”.
Dalam kerangka ini, tafsir reflektif filosofis-sufistik yang mengetengahkan empat model jalan (intelektual, moral, spiritual, dan praktis sehari-hari) sangat relevan dijadikan panduan bagi pergaulan masyarakat di dunia maya. Ada tiga relevansi dari tafsir reflektif filosofis-sufistik atas QS. Al-Fatihah [1]: 6, yang berkontribusi terhadap lingkaran kebaikan pergaulan masyarakat di dunia maya, yaitu:
1. Mengembalikan kedalaman makna
Dunia digital bersifat dangkal; tafsir filosofis menegaskan kedalaman pemaknaan reflektif atas realitas.
2. Menanamkan kesadaran diri
Sufisme membangun muhasabah dan tazkiyah—penawar ego digital. Menyadari diri yang lemah dan membutuhkan jaringan sosial kebajikan.
3. Menghidupkan akhlak dari dalam diri, bukan paksaan dari luar
Hidayah menumbuhkan karakter, bukan sekadar kepatuhan teknis.
Penutup: Hidayah sebagai Cahaya bagi Peradaban Digital
Era digital membutuhkan bukan hanya kecakapan teknologi, tetapi kedalaman moral. Tanpa hidayah, manusia akan tersesat dalam banjir informasi. QS. al-Fātiḥah [1]: 6 mengingatkan bahwa manusia membutuhkan petunjuk Ilahi agar mampu menapaki al-ṣirāṭ al-mustaqīm dalam dunia yang bergerak cepat dan tidak pasti.
Dengan memadukan pandangan para mufassir klasik dan modern di atas, dengan pendekatan filosofis–sufistik, hidayah menjelma sebagai fondasi akhlak global—cahaya yang menuntun akal, jiwa, dan tindakan di ruang digital. Dengan misi peradaban digital Qur’ani, yaitu taat kepada jalan lurus yang dikandung di dalam QS. al-Fātiḥah [1]: 6.